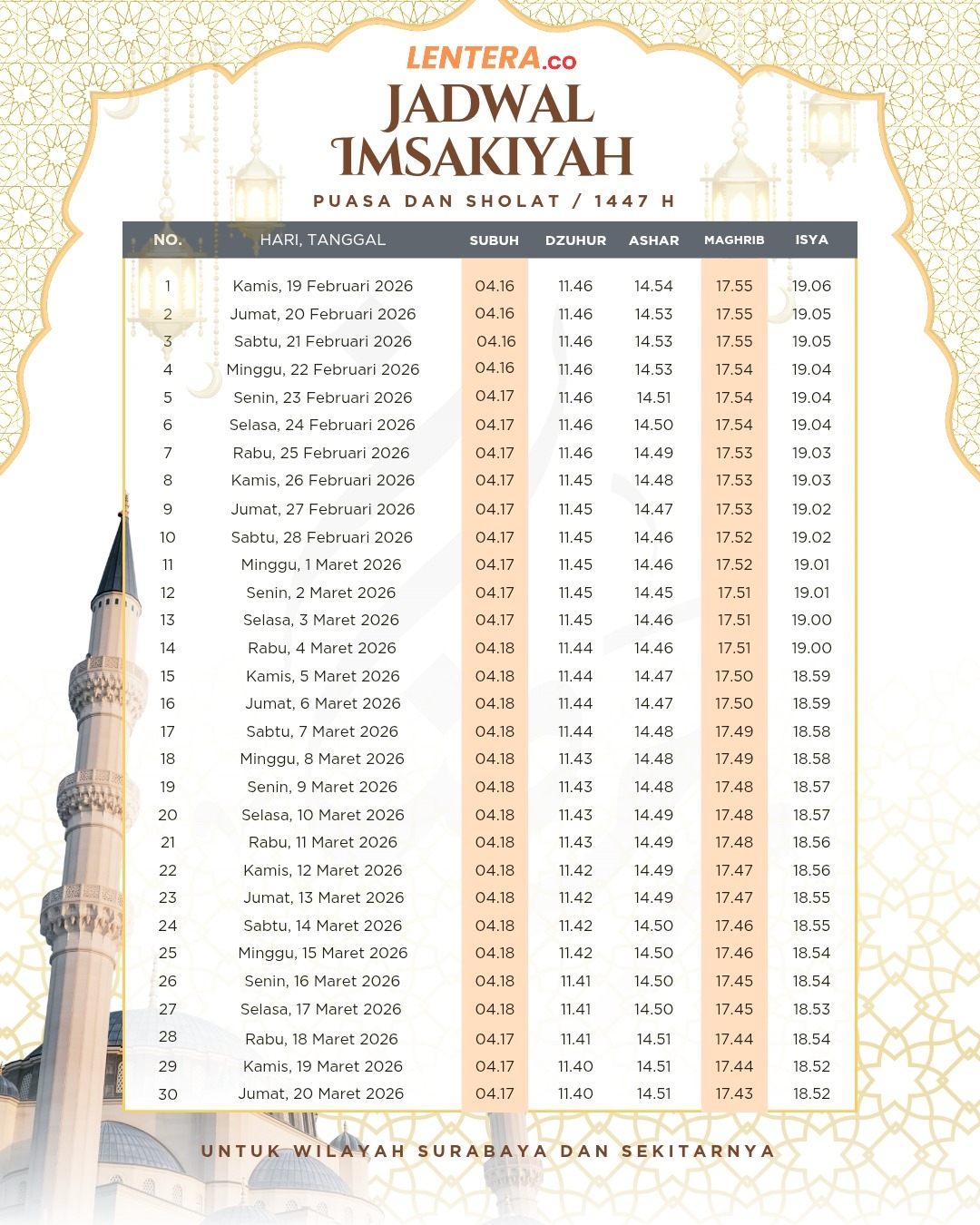JAKARTA (Lenteratoday) - "Gaji kami tetap, tetapi harga kebutuhan naik terus. Bagaimana kami bisa bertahan?" ujar Dina, seorang pegawai swasta, ditemui di Jakarta, Sabtu (29/12/2024).
Sikap yang sama juga dintunjukkan Agus, pegawai salah satu pegawai Badan Usaha Milik Negara, kendati tidak sefrontal Dina. Dia memilih langsung berpikir solutif. ”Jualan lagi yuk! Gaji tidak naik, malah pajak yang naik,” katanya.
Begitulah contoh kecil bagaimana kelompok pekerja bereaksi atas kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025. Reaksi mereka menggambar beratnya situasi ekonomi yang mereka hadapi.
Tetapi toh kebijakan sudah dibuat. Kenaikan PPN ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk meningkatkan pendapatan negara.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat basis penerimaan pajak dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
"Langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal dalam menghadapi tantangan ekonomi global," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Tarif PPN sebelumnya sebesar 11% telah berlaku sejak tahun 1984, menjadikan kenaikan ini sebagai salah satu perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia.
Naiknya tarif PPN ini dapat dipahami sebagai solusi untuk memperlebar ruang fiskal anggaran negara. Beban utang yang terus bertambah dalam 10 tahun terakhir telah mempersempit anggaran yang bisa dialokasikan untuk program pembangunan.
Di bawah pemerintahan Jokowi, rasio utang terhadap PDB meningkat signifikan, terutama karena pembiayaan proyek infrastruktur besar-besaran dan belanja pandemi COVID-19. Pada akhir masa jabatan Jokowi, total utang pemerintah mencapai lebih dari Rp7.800 triliun, atau sekitar 40% dari PDB, masih dalam batas aman tetapi menimbulkan tekanan fiskal.
Pemerintah memiliki target untuk menurunkan defisit anggaran hingga di bawah batas 3% dari PDB, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kenaikan PPN merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit melalui utang baru.
Penolakan yang Meluas
Kebijakan ini segera memicu reaksi luas dari masyarakat, pakar ekonomi dan para pelaku usaha. Pasalnya naiknya tarif PPN bakal berdampak pada harga barang dan jasa yang berpotensi mengerek angka inflasi.
Sejumlah pelaku usaha menyatakan kekhawatiran mereka terhadap dampak kenaikan ini pada daya beli masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.
Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan PPN 12% dengan alasan dapat membebani biaya produksi.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menjelaskan, meski bahan pokok tidak dikenakan PPN 12% tetapi barang lain dalam rantai produksi tetap terdampak. Sebut saja bahan baku yang turut mengalami kenaikan harga atas pengenaan pajak dimaksud.
Dia mengingatkan, kebijakan PPN 12 persen juga akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang premium seperti beras, buah-buahan, ikan, udang serta daging.
Begitu pula dengan layanan kesehatan premium di rumah sakit VIP, pendidikan standar internasional serta listrik untuk pelanggan dengan daya 3.600-6.600 Volt Ampere.
"Kita berharap pemerintah lebih bijaksana melihat kondisi ke depan. Kalau kita lihat Vietnam malah jadi delapan persen, ini di kita kok malah naik," katanya, Sabtu (29/12/2024)
Pengusaha, kata dia, merasakan dua hantaman hebat dalam waktu hampir bersamaan setelah sebelumnya pemerintah juga menaikan umpah minimum sebesar 6,5 %.
Keluhan yang sama disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey. Menurut dia, daya beli masyarakat terpukul dengan kenaikan PPN.
"Kami memprediksi akan ada penurunan konsumsi dalam jangka pendek karena masyarakat perlu menyesuaikan pengeluaran mereka," kata dia.
Beberapa tokoh juga secara tegas menolak kenaikan ini karena dampaknya terhadap masyarakat. Salah satunya adalah anggota DPR dari Komisi XI, Hendrawan Supratikno, yang menyatakan bahwa kenaikan PPN berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi.
"Di tengah kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, kebijakan ini tidak tepat. Lebih baik pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari pajak yang sudah ada," tegas Hendrawan.
Ekonom senior Bhima Yudhistira juga mengkritik kebijakan ini dengan alasan bahwa daya beli masyarakat masih sangat rapuh. "Kenaikan ini bisa memicu inflasi lebih tinggi dan membuat konsumsi domestik tertekan. Padahal, konsumsi domestik adalah motor penggerak utama perekonomian kita," ungkap Bhima.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, turut menyampaikan keberatannya. Menurutnya, kebijakan ini dapat memperparah kesenjangan sosial. "Pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan efisiensi belanja negara dan perbaikan pengawasan pajak dibandingkan membebani masyarakat dengan kenaikan PPN," jelas Tauhid.
Tren kenaikan harga barang dan jasa menyusul naiknya pajak juga terjadi di sejumlah negara, seperti Jerman dan Jepang, kenaikan PPN dalam beberapa tahun terakhir terbukti memicu inflasi jangka pendek.
Di Jerman, kenaikan PPN dari 16% menjadi 19% pada tahun 2007 menyebabkan lonjakan harga barang konsumsi. Hal serupa terjadi di Jepang pada 2014 ketika tarif pajak dinaikkan dari 5% menjadi 8%, yang memengaruhi daya beli masyarakat dan menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga.
Terobosan untuk Menggeser PPh
Meski begitu, kenaikan PPN sangat membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan PPN membuat pemerintah lebih leluasa mengatur belanja APBN untuk menghadirkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kenaikan rasio pajak tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengatur belanja negara di APBN. Jadi, pemerintah punya keleluasaan melakukan redistribusi pajak untuk pembangunan dan mensejahterakan rakyat," jelasnya.
Dia juga menilai kenaikan tarif PPN tersebut menjadi salah satu terobosan untuk menggeser porsi penerimaan pajak dari PPh (Pajak Penghasilan) ke PPN.
Prianto mengatakan salah satu tren kebijakan pajak di dunia saat ini adalah penurunan tarif PPh badan. Tujuannya utk menarik investasi asing.
Namun, sebagai konsekuensinya ada tax competition di tarif PPh Badan. Salah satu bentuknya adalah pemberian tax holiday. Istilah yang kerap muncul adalah 'race to the bottom', sehingga banyak negara berlomba menurunkan tarif PPh Badan.
Menurut dia, penerapan pajak PPN lebih simpel dan risiko praktik penghindaran pajak jauh lebih rendah. Sehingga tarif pajak langsung dikenalan atas nilai transaksi.
"Jadi, tujuan peningkatan tarif PPN dan perluasan objek PPN di antaranya memang untuk menggantikan tren penurunan penerimaan PPh Badan. Salah satu tren kebijakan pajak di dunia saat ini adalah penurunan tarif PPh badan. Tujuannya untuk menarik investasi asing," terang Prianto.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Kendati terus mendapatkan kritik, pemerintah bergeming. Untuk mengurangi dampak kenaikan, pemerintah telah mengumumkan sejumlah langkah mitigasi. Program Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi energi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Selain itu, pemerintah menjanjikan peningkatan layanan publik sebagai hasil dari kenaikan pendapatan pajak.
"Kami ingin masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini, baik melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan," tegas Sri Mulyani.
Bagaimana pun juga, kenaikan PPN menjadi 12% tidak terelakkan dalam upaya memperkuat keuangan negara. Pengalaman Jerman dan Jepang menunjukkan kenaikan PPN memerlukan langkah mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampak negatifnya pada masyarakat,
terutama kelompok rentan. Efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Sumber: Antara, Detik, Kompas, CNN | Editor : M. Kamali