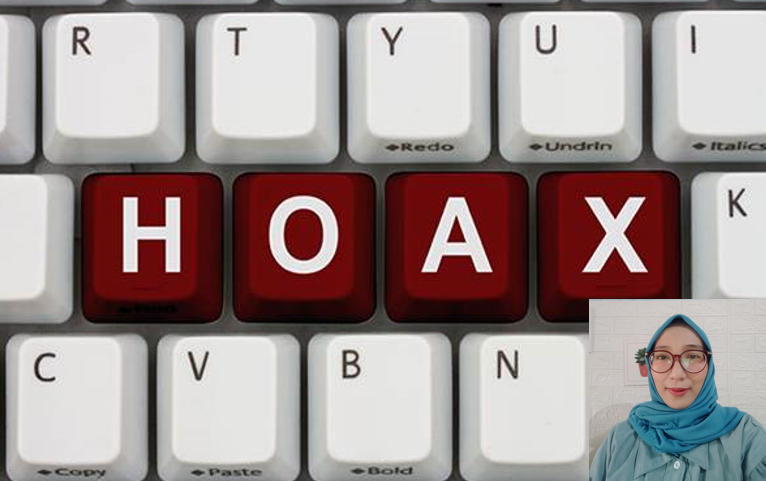
Oleh: Agustina Widyawati (*)
Abstrak
Setiap era dan kebudayaan memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang digunakan sebagai referensi untuk menafsirkan dan memahami lingkungan dan isinya, dan digunakan sebagai alat untuk memanfaatkan, mengolah, dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan manusia kebutuhan. Saat ini, perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat sekali. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) masyarakat mendapatkan berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam memperoleh informasi. Tak hanya melalui media konvensional tapi juga kehadiran media sosial (medsos).
Keberadaan Medsos yang tidak berada dalam pengawasan Dewan Pers dengan Kaidah Jurnalistik dan Kode Etiknya berdampak buruk dengan membanjirnya berita bohong atau hoax. Hoax berseliweran di dunia maya dan menjadi buah bibir dunia nyata hingga mempengaruhi pola pikir dan keputusan masyarakat. Saat virus Covid-19 melanda, bukan hanya pandemi penyakit yang menjadi ancaman. Tapi infodemi menjadi ‘wabah’ baru yang tak kalah berbahaya. Infodemik adalah portmanteau dari ‘informasi’ dan ‘epidemi’ yang mengacu pada penyebaran yang cepat dan jauh dari informasi yang tidak/belum tentu keakuratannya dan bahkan banyak yang tidak akurat.
Menggunakan metode analisis deskriptif dengan teori-teori komunikasi dan filsafat untuk mengidentifikasi masalah komunikasi modern seperti berita bohong atau hoax di media sosial. Pengumuman hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna media sosial baik individu, komunitas, lingkungan akademik, maupun pemerintah.
Pendahuluan
Seiring perkembangan teknologi informasi terutama digitalisai yang melahirkan media sosial (medsos), banjir informasi bak tak terbendung lagi. Kita nyaris tak berdaya untuk menghadapi dengan sikap kritis dalam menyaring serta membagi informasi. Daya kritis kita seringkali tumpul, tergantikan oleh sikap menerima informasi dengan mengabaikan kenyataan faktualnya.
Padahal, ketergantungan pada representasi informasi secara tidak kritis ini membuat kita sangat rentan terhadap semua jenis hoax yang secara tidak disadari meruntuhkan kredibilitas kita sebagai anima rationale. Yaitu istilah Aristoteles yang mengatakan artinya manusia dapat menata dan mampu mengatur perilaku dengan menggunakan akal waras dan kehendak bebas.
Kredibilitas yang dimaksudkan di sini adalah kualitas kepercayaan atau penerimaan sesuatu sebagai benar, nyata, atau jujur. Maka seperti metode critical thinking (berpikir kritis) oleh Reynolds (2011), kredibilitas hanya dapat dibangun melalui kritik terhadap kenyataan dan sesuai fakta, oleh karena itu kemudian layak dipercaya.
Definisi hoax/hoaks menurut Lexico Oxford Dictionary yaitu: A humorous or malicious deception. Secara bebas bisa diartikan sebagai ‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat’. Sedangkan hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai informasi bohong.
Hoax ini makin banyak ditemukan pada era post-truth. Jika dicermati istilah post-truth berdasarkan etimologi berasal dari Bahasa inggris. Oxford Dictionary menyatakan ‘post’ artinya ‘after’ (setelah) sebagaimana dijelaskan dalam kosa kata ‘post- modern’ yang diartikan sebagai ‘review of an event after it has happened’ (simpulan atas sebuah peristiwa itu terjadi) (Manser, 1996) dan truth berarti ‘quality or state of being true’ (kualitas atau dalam keadaan benar atau kebenaran) (Manser, 1996). ‘Truth’ ini merupakan kata benda dari kata sifat ‘true’. Sehingga post-truth artinya setelah atau pasca kebenaran karena dalam rentang masa ini penggunaan akal yang melandasi kebenaran dan pengamatan fakta sebagai basis pengukuran obyektifitas seakan-akan tak penting dalam memengaruhi opini, pemikiran maupun perilaku publik.
Steve Tesich sebagai orang pertama yang menggunakan istilah ‘post-truth,’ dalam artikel berjudul The Government of Lies (1992) yang dimuat majalah ‘The Nation’ menggambarkan bagaimana skandal Watergate dan Perang Teluk Persia dapat membuat tenang dan nyaman warga Amerika Serikat meskipun dua insiden keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa dan kemenangan Donald Trump dalam kontestasi politik di Amerika Serikat pada tahun 2016 yang melatarbelakangi kemunculan istilah ‘post-truth’ secara nyata dipenuhi banyak kebohongan.
Fenomena yang muncul berikutnya dari kedua insiden itu adalah rasionalitas telah tergeser oleh emosionalitas. Steve Tesich menuliskan bahwa opini warga negara Amerika Serikat digiring melalui pernyataan emosional, bukan dengan fakta yang sebenarnya. Maksud Tesich menunjukkan bila masyarakat yang hidup dalam kebohongan bukanlah hal tabu karena kebohongan-kebohongan yang disebarkan dapat menyentuh aspek emosional. Efeknya memang membuat buram kebenaran rasional yang pada gilirannya masyarakat menemukan kesulitan dalam memperoleh kebenaran faktual.
Efek demikian tidak saja memengaruhi komunitas pada belahan dunia tertentu, namun juga telah merasuki rasionalitas dan budaya publik di Indonesia. Teknologi digital berupa media sosial berbasis internet turut mengakselerasi pengaruh ‘post-truth.’ Pada satu sisi, pengaruh teknologi digital mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, dan memperlancar arus komunikasi sosial melalui media sosial daring dengan beraneka flattform, seperti facebook, whatsapp, twitter, dan lain-lain.
Berdasarkan kondisi tersebut yang tidak berlandaskan pada kebenaran faktual, kondisi masyarakat diperparah dengan minimnya basis epistemologis dalam masyarakat untuk memperoleh kebenaran. Masyarakat tidak bisa memberikan benang merah atau cut off yang jelas antara kebenaran, dan bukan karena terbiasa menerima kebenaran sebagai sebuah produk jadi. Maka tujuan penulisan ini adalah membahas disiplin ilmu filsafat terkait pengungkapan kebenaran perspektif filsafat kemudian menyuguhkan cara pengimplementasian teori kebenaran persepektif filsafat dalam hal penyaringan berita agar masyarakat dapat menerima kebenaran yang semestinya.
Jenis penulisan yang digunakan dalam karya ilmah ini adalah penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulisan kualitatif ialah penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis yang bertujuan memberikan gambaran keadaan, sistem ataupun inovasi secara sistematis.
Jenis data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara kedua. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan ini adalah dengan metodekepustakaan, dokumenter, dan intuitif subjektif.
Proses analisis data dilakukan dengan menyajikan data-data yang terkumpul dan kemudian dipaparkan dalam pembahasan. Disamping itu, sintesis dilakukan dengan menggunakan studi silang (cross link) antara data yang terkumpul dan konsep yang ditawarkan. Kemudian dapat diambil titik utama yang diolah menjadi beberapa kesimpulan dan saran. Proses analisis data pada karya ilmiah ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan pemaparan dan penarikan kesimpulan (conclution drawing and verfication).
Tulisan ini hendak menyingkap labirin hoax dan infodemiyang bersemayam di media sosial terkait pandemi Covid-19. Istilah labirin itu sendiri, sebagaimana dipahami penulis adalah sesuatu yang simpang siur, rumit, dan berbelit-belit. Berdasarkan pemahaman ini, maka hoax dalam tulisan ini dipandang sebagai fenomena atau bahkan persoalan yang penyelesaiannya berhadapan dengan kesimpangsiuran, kerumitan, dan berbelit-belit.
Pembahasan
Dalam era digital, seperti dikutip dari Nasrullah (2014) menyebut khalayak bisa menjadi consumer sekaligus produsen informasi (Prosumer), atau Burn (2010) menyebutkan dengan istilah berbeda Produsage akronim dari kata bahasa Inggris; Producer (Produser) dan Usage (Pengguna).
Fenomena Prosumer maupun Produsage telah menempatkan masyarakat sebagai khalayak komunikasi tidak lagi pada posisi objek yang dideterminasi oleh media massa arus utama Pada sisi ini , melalui teknologi dan media itu, masyarakat memperoleh kemudahan dalam menciptakan, mengunggah, menggandakan, memanipulasi, menyunting baik tulisan maupun gambar dan video tanpa disertai tanggungjawab atas dampak destruktif yang ditimbulkannya.
Teknologi yang melahirkan media sosial seperti facebook, whatsapp, twitter, Instagram telah dengan luar biasa mengubah budaya masyarakat dunia. Tak sekadar sebagai eksistensi diri, lebih jauh lagi orang dapat mempersuasi dan mengubah cara pandang orang lain. Bahkan melalui media sosial, bisa mengajak orang menjadi baik dan buruk.
Seringkali hoax menjejali beranda para pengguna facebook dan instagram, muncul dalam kicauan di twitter dan tersebar meluas melalui Whatsapp dengan berbagai tujuan, seperti menebarkan ketakutan, memberikan terror, rasa takut, mengganggu keamanan menyulut kebencian yang akhirnya akan mengotak-ngotak masyarakat dan tak jarang berujung menjadi ketegangan.
Pada saat Covid-19 (corona virus disease-19) melanda seluruh dunia, tak hanya virus yang menyebar, tapi berita membanjiri semua media informasi baik media maupun media sosial. Walhasil bukan hanya pandemi, tapi dunia termasuk di Indonesia juga diserang oleh infodemi.
WHO mendifinisikan infodemik sebagai kelebihan jumlah informasi yang beredar dimana beberapa diantaranya akurat dan beberapa ada yang tidak. Infodemik ini menyulitkan orang untuk mendapatkan sumber yang akurat, kredibel dan dapat diandalkan sebagai pedoman. Jika kita perhatikan, informasi yang menyebar ke masyarakat disampaikan oleh orang yang bukan ahlinya, sehingga hanya merupakan opini semata.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dikutip dari Kantor Berita Antara menyebutkan terdapat sebanyak 1.991 isu hoaks Covid-19 pada 5.131 unggahan media sosial selama kurun waktu 23 Januari 2020 hingga 18 November 2021. Kesimpangsiuran berita saat Covid-19 masuk di Indonesia mulai dari informasi penyebaran virus tersebut sampai pencegahan dan penanganan Covid-19.
Berita Hoax yang tersebar tersebut menimbulkan keonaran di masyarakat. Salah satunya, berita Hoax mengenai pencegahan penularan Covid-19 pada pertengahan Maret 2020 oleh akun facebook Cinta Bella "Bawang merah itu ternyata menyedot virus dan kuman lalu memfokuskannya masuk dalam intra sel, lalu dicerna dalam vakuola dan membunuhnya. Bukan hanya virus saja, tapi juga bakteri, kuman, semuanya terkumpul di situ dalam keadaan sudah in-aktif atau mati," tulisnya.
Cinta Bella menceritakan, sang dokter melakukan sendiri percobaan denganmeletakkan beberapa potongan bawang merah di samping ranjang pada pasiennyayang menderita radang paru-paru berat atau pneumonia. Keesokan paginya,bawang merah tersebut berubah berwarna hitam. Di bagian akhir ceritanya, CintaBella mengajak pembaca untuk memasang bawang merah yang dikupas di setiapruangan rumah.
Melalui laman resmi Kominfo, dijelaskan bahwa bawang merah yang dapat mengikat virus adalah mitos, seperti yang dijelaskan oleh NationalOnion Association (NOA). NOA merupakan organisasi yang mewakili petani,pedagang, eksporter, dan importer bawang merah di AS yang sudah berdiri sejak 1913. Mereka juga mengatakan bahwa mitos bawang merah dapat mengikat virusternyata mitos yang sudah beredar di seluruh dunia.
Contoh lain yaitu Berita Hoax mengenai Rumah Sakit yang sengaja ‘mengcovidkan’ pasien. Kabar viral itu disampaikan oleh akun @BalqisRrzq(Sandekala) pada 20 Juli 2020 pukul 08.48 WIB. PERSI mengumpulkan sejumlahtuduhan yang disampaikan akun tersebut. Salah satu yang disampaikan oleh akuntersebut adalah adanya seorang pasien di RS Wiyung Sejahtera, yang tidakmenerima hasil tes swab positif virus Corona (Covid-19) tetapi dinyatakanpositif Covid-19.
Selain itu, akun tersebut dinilai telah menuduh RS Wiyung merekayasa hasil positif Corona demi mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan rincian Rp 200 juta per pasien positif dan RP 350 juta per pasien Coronayang meninggal dunia. "Sampai laporan ini disusun, yang bersangkutanmenyampaikan bahwa tuduhan terhadap RS Wiyung, RS Siloam, dan RS Mayapada yang 'mengcovidkan pasien dengan tujuan uang bantuan ratusan juta ' didasarkan pada 'hanya dapat dari hasil teman ayah saya yang katanya orang dinkes'," kata Anjari. Atas hal itu, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyimpulkan tuduhan yangdisampaikan Balqis tak berdasar dan fitnah.
Telah dipaparkan sebelumnya bahwa hoax saat ini makin banyak ditemukan pada era post-truth. Dalam membuat dan memperoleh informasi lebih diutamakan terbentuknya opini publik dengan mengeksploitasi sisi emotif dan keyakinan personal masyarakat untuk mencapai target tertentu tanpa mengindahkan kebenaran faktual.
Sementara di sisi lain, filsafat sejak era Yunani kuno selalu fokus untuk mencari dan merumuskan kebenaran sebagai orientasi arah kehidupan manusia. Kendati demikian, kebenaran dalam filsafat tidak pernah mewujud dalam wacana tunggal. Kebenaran selalu mewujud dalam berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan.
Kebenaran dalam perspektif rasionalisme tentu akan berbeda dengan kebenaran dalam perspektif penganut empirisme. Silang pendapat antara rasionalis dan empirisis dalam melihat kebenaran bermuara pada pertanyaan dasar tentang sumber pengetahuan manusia. Dalam diri manusia, manakah dia antara akal atau panca indera yang merupakan sumber utama pengetahuan manusia? Selain cakupan dan validitas pengetahuan, pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan menjadi salah satu topik, dalam salah satu cabang filsafat, yaituepistemologi.
Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengandaian-pengandaian dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. (Gallagher,1994) Pada periode awal tradisi filsafat Yunani, epistemologi belum menjadi perhatian utama para filosof, kajian mereka lebih bersifat ontologis.
Para filosof pada era ini masih terfokus pada dimensi ontologis dengan mempertanyakan manakah realitas yang sejati, dunia fisik seperti yang diyakini oleh pengusung materialisme ataukah dimensi metafisik seperti yang diusung para idealis. Baru kemudian pada masa Kant, perhatian manusia mulai bergeser dari pertanyaan ontologis mengenai apa itu realitas ke arah yang lebih epistemologis dengan mempertanyakan bagaimana pengetahuan tentang realitas bisa diakses oleh manusia.
Pada awalnya, pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan (the origin of knowledge) dan teori tentang kebenaran (the theory of truth) pengetahuan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan suatu pertanyaan apakah pengetahuan itu bersumber pada akal pikiran semata, pengalaman indera, kritik atau intuisi.
Sementara itu, pembahasan yang kedua terfokus pada pertanyaan apakah ‘kebenaran’ pengetahuan itu dapat digambarkan dengan pola korespondensi, koherensi atau praktis-pragmatis. Selanjutnya, pembahasan dalam epistemology mengalami perkembangan, yakni pembahasannya terfokus pada sumber pengetahuan, proses dan metode untuk memperoleh pengetauan, cara untuk membuktikan kebenaran pengetahuan, dan tingkat-tingkat kebenaran pengetahuan.
Harold Titus menyebutkan tiga persoalan besar yang diperdebatkan dalam diskursus epistemologi. Pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan yang benar itu dan bagaimana kita mengetahuinya? Kedua, apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apakah ia bersifat obyektif, sebagaiman para penganut obyektivisme yang menekankan pengetahuan itu bisa ada di luar pikiran kita, ataukah pengetahuan itu bersifat subyektif, sebagaimana para pengusung subyektivisme yang menyatakan pengetahuan hanya ada sejauh pikiran manusia dapat mencapainya? Ketiga, apakah pengetahuan kita bersifat benar (valid)?
Pada persoalan ini, para filosof berkutat dengan validitas kebenaran dan cara untuk menguji kebenaran pengetahuan tersebut, baik melalui verifikasi maupun falsifikasi. Untuk dapat merumuskan kebenaran syarat pertama yang harus terpenuhi adalah jaminan bahwa pengetahuan yang kita peroleh harus berasal dari sumber yang benar. Pada persoalan ini, para filosof berbeda pendapat tentang sumber pokok pengetahuan. Terjadi silang pendapat antara idealisme dan realisme, antara rasionalisme dan empirisisme.
Sejarah mencatat bahwa Plato dan Aristoteles merupakan pelopor awal perseteruan antara rasionalisme dan empirisisme. Bagi Plato, pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan bersifat a priori dan bersumber pada akal. Ia lebih mengungulkan dunia idea yang bersifat tetap sebagaimana rumus dan hukum universal matematika tinimbang dunia pengalaman empirik.
Diketahui bila kebenaran dalam filsafat memiliki berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Berbagai perspektif tersebut kemudianmelahirkan berbagai jenis teori kebenaran. Pada bagian ini, akan dibahas berbagai teori kebenaran yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi filsafat.
Purwadarminta (Fautanu,2012) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa kebenaran itu adalah 1). Keadaan (hal dan sebagainya) yang benar (cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. 2). Sesuatu yang benar (sugguh-sugguh ada, betulbetul hal demikian halnya, dan sebagainya). Misalnya kebenaran-kebenran yang diajarkan agama. 3). Kejujuran, kelurusan hati, misalnya tidak ada seorangpun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu.
Sedang menurut Abbas Hamami (2003) , kata “kebenaran” bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkrit maupun abstrak. Jika subyek hendak menuturkan kebenaran artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia (subyek yang mengetahui) mengenai obyek. (Susanto, 2011)
Jadi, kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan, pengetahuan berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Berikut ini adalah teori-teori kebenaran.
1. Teori Korespondensi (Correspondence Theory of Truth)
Teori kebenaran korespondensi, Correspondence Theoryof Truth yang kadang disebut dengan accordance theory of truth, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataanpernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesuaian (correspondence) antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyaan atau pendapat tersebut.(Suaanto,2011) Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya.
Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, Moore, dan Ramsey. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell (1972-1970).(Susanto,2011) Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal (sebelum abad Modern) mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya.( Muhadjir,2001)
Problem yang kemudian muncul adalah apakah realitas itu obyektif atau subyektif? Kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada dihadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antra pernyataan tentan sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misal, Surabaya ibu kota Jawa Timur. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Surabaya memang ibu kota propinsi Jawa Timur. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan.
Signifikansi teori ini terutama apabila diaplikasikan pada dunia sains dengan tujuan dapat mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada sesuatu secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihatnya itu benar-benar nyata terjadi. Sebagai contoh, gunung dapat berjalan. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan ini harus diteliti dengan keilmuan yang lain yaitu ilmu tentang gunung (geologi), ternyata gunung mempunyai kaki (lempeng bumi) yang bisa bergerak sehingga menimbulkan gempa bumi dan tsunami.
Dengan demikian, sebuah pertanyaan tidak hanya diyakini kebenarannya, tetapi harus diragukan dahulu untuk diteliti, sehingga mendapatkan suatu kebenaran hakiki.
2. Teori Koherensi (Coherence Theory of Truth)
Pembuktian secara berulang-ulang pada teori korespondensi pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang pada umumnya berwujud sebagai kebenaran umum (general truth). Matahari terbit dari arah timur. Pernyataan tersebut merupakan sebuah kebenaran umum karena sudah diyakini benar. Kita tidak perlu menunggu hingga esok pagi untuk membuktikan secara faktual bahwa matahari benar-benar terbit dari ufuk timur. Aksioma atau postulat adalah sebuah pernyataan yang dianggap sudah terbukti benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. Karena sifat itulah ia dijadikan sebagai dasar dalam disiplin ilmu matematika dan bisa digunakan untuk membuktikan apakah pernyataan lain benar atau tidak.
Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbuktibenar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan (kontradiksi) antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Sebagai contoh, di dalam disiplin ilmu matematika terdapat postulat bahwa jumlah sudut semua jenis bangun ruang segitiga berjumlah 180°. Jika ada satu pernyataan bahwa terdapat satu bentuk segi tiga yang jumlah sudutnya 210°, maka tanpa harus menyaksikan bukti faktual segitiga tersebut kita bias menyatakan bahwa pernyataan orang tersebut tidak benar karena ia bertentangan dengan postulat. Pernyataan orang tersebut memiliki kontradiksi denganpostulat yang sudah ada.
Perbedaan teori ini dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi dasar kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada, sedangkan pada teori koherensi pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Contoh lainnya, seseorang memberi pernyataan bahwa di dalam kolam alun-alun kota terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup.
Menurut teori korespondensi, untuk menentukan pernyataan tersebut benar atau tidak, kita harus menunggu fakta apakah di dalam kolam tersebut terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup atau tidak. Sementara menurut teori koherensi, tanpa menunggu fakta, kita bisa menentukan pernyataan orang tersebut tidak benar karena bertentangan dengan aksioma yan sudah ada sebelumnya bahwa ikan hiu adalah jenis ikan air asin (laut). Tidak logis jika ikan air asin bisa hidup dalam air kolam alun-alun kota yang merupakan kolam air tawar.
3. Teori Pragmatis (The pramagtic theory of truth.)
Teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta obyektif dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan obyek pengetahuan metafisik. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positivis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna (meaningless) karena ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris.
Menurut kaum pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Neraka ada bagi manusia yang berperilaku jahat. Terlepas dari ketiadaan bukti empiris tentang neraka, pernyataan itu bisa dianggap sebagai pernyataan yang benar karena memiliki manfaat dalam menurunkan angka kejahatan.
Terkait dengan teori kebenaran, Charles Pierce, salah satu tokoh pragmatism menjelaskan bahwa kriteria berlaku dan memusaskan sebagai dasar kebenaran dalam pragmatisme digambarkan secara beragam dalam berbagai sudut pandang.(Lubis,) Beragamnya sudut pandang dalam menentukan hasil yang memuaskan akan berujung pada beragamnya standar kebenaran. Kebenaran menurut saya belum tentu benar menurut orang lain karena apa yang memuaskan bagi saya belum tentu memuaskan bagi orang lain. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat teori pragmatisme rentan terjebak dalam relativisme. Inilah salah satu dari beberapa kritik yang diarahkan pada teori pragmatisme.(Jujun,
4. Teori Performa (The performance theory of truth)
Teori ini berasal dari John Langshaw Austin(1911-1960) dan dianut oleh filsuf lain sepertiFrank Ramsey, dan Peter Strawson. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa “benar”dan “salah” adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu (deskriptif). Proposisi yang benar berarti proposisi itu menyatakan sesuatu yang memang dianggap benar. Demikian sebaliknya. Namun justru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini.( Jujun,2000)
Teori performatif menjelaskan, suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga “tindak bahasa” mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. (Lubis,2015) Misalnya, “Dengan ini saya mengangkat anda sebagai manager perusahaan “PT.A”. Dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru yaitu anda sebagai manager perusahaan “PT. A”, tentunya setelah SKnya turun. Di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu. Dengan pernyataan itu suatu penampilan atau perbuatan (performance) dilakukan.
Teori ini dapat diimplementasikan secara positif, tetapi di pihak lain dapat pula negatif. Secara positif, dengan pernyataan tertentu, orang berusaha mewujudkan apa yang dinyatakannya.(Susasanto,2011) Misal, “Saya bersumpah akan menjadi dosen yang baik”. Tetapi secara negatif, orang dapat pula terlena dengan pernyataan atau ungkapannya seakan pernyataan tersebut sama dengan realitas begitu saja. Misalnya, “Saya doakan setelah lulus kamu menjadi orang yang sukses”, ungkapan ini bagi sebagian orang adalah doa padahal bisa saja sebagai basa-basi ucapan belaka. Bisa jadi kitasemua terjebak dengan pernyataan seperti itu seolah-olah dengan dengan pernyataanpernyatan itu tercipta realitas seperti yang dinyatakan. Padahal apa yang dinyatakan, belum dengan sendirinya menjadi realitas.(Suseno,2000)
Teori kebenaran consensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Penulis buku The Structure of Scientific Revolutions ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. (Kuhn,1962) Pada perkembangannya, akan muncul beberapa anomali yang membuat konsepsi kebenaran tersebut dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya, akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan pergeseran paradigma (shifting paradigm) dalam masyarakat ilmiah. Singkat kata, perkembangan imu pengetahuan ditandai dengan adanya pergeseran paradigma lama yang digantikan oleh paradigma baru. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat (social acceptance) terhadap sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah.
Berdasarkan konsepsi Kuhn di atas, sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan (konsensus) dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Inilah yang disebut teori kebenaran konsensus. Teori ini selanjutnya dikembangkan juga oleh Jurgen Habermas melalui konsep pemikirannya tentang komunikasi rasional. Senada dengan Kuhn, menurut Habermas, kebenaran sebuah pernyataan ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan di antara partisipan rasional komunikatif dalam sebuah diskursus.(Suseno,2000)
Pada hakekatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengankarakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia; baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan.(Bakhtiar
Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama denngan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab Suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentuk kebenaran mutlak.
Adanya berbagai teori kebenaran yang telah dipaparkan sebelumnya, menunjukkan bahwakebenaran perspektif filsafat bersifat multikultural. Adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang validitas kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam oposisi biner, hitam-putih, benar-salah. Ada kemungkinan bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan bersifat gradatif. Semakin banyak ia sesuai dengan teori kebenaranyang ada, semakin tinggi validitas kebenaran yang dikandungnya. Demikian juga sebaliknya.
Tantangan selanjutnya yang akan dihadapi adalah sejauh mana teori-teori kebenaran tersebut bisa diimplementasikan dalam menyaring berita palsu. Tentu saja penerapan teori-teori tersebut bergantung pada kondisi obyek kebenaran itu sendiri. Adapun aktualisasinya adalah sebagai berikut: Teori korespondensi misalnya, bisa diterapkan selama obyek kebenaran bersifat faktual dan bisa diakses secara langsung melalui panca indera. Jika tidak bisa diakses langsung, masih terdapat opsi teori kebenaran lain yang bisa diterapkan.
Dalam konteks dunia maya, pembuktian kebenaran dilakukan melalui gambar atau video.Tetap ada kemungkinan bahwa gambar atau video tersebut adalah palsu sehingga diperlukan fakta lain sebagai pendukung atau pembanding. Selain itu, dibutuhkan penjelasan lebih lanjutdari pakar telematika untuk membuktikan validitas data faktual (gambar atau video) tersebut.
Dalam hal ini, penerapan teori performatif jelas signifikansinya. Teori performatif juga bisa diterapkan untuk menyaring sumber berita. Jika terdapat berita yang terkait dengan isu-isutertentu, akan lebih bijak jika kita melakukan konfirmasi kepada pihak yang memiliki otoritas di bidang tersebut.
Ketika kita mendapatkan dua atau lebih pernyataan atau yang bertentangan, makapenerapan teori koherensi sangat diperlukan. Pernyataan yang dianggap benar tentu saja adalahpernyataan yang konsisten dengan berita lain yang sudah terbukti sebelumnya sebagai beritayang benar. Berdasarkan asas kemanfaatan, kita tentu saja boleh membagikan berita yangdiasumsikan akan bermanfaat bagi orang lain, tentu saja dengan catatan bahwa berita tersebuttelah melalui uji korespondensi, koherensi ataupun uji performatif sebelumnya.
Teori konsensus bisa diterapkan untuk menyaring situs atau portal berita yang tidakmencukupi syarat bagi terbentuknya komunikasi rasional. Situs atau portal berita semacam inibiasanya dicirikan dengan adanya klaim kebenaran dalam reportase beritanya dan tidakmenyajikan fakta yang berimbang.
Sedangkan teori agama malarang sikap bebas berekspresi yang digunakan untukmengumbar kebencian dan permusuhan. Agama memberikan pembatas atau pengendalianhukum dan moral terhadap kebebasan tersebut. Dengan demikian agama merumuskan akan pentingnya tabayyun (cek dan ricek) sebelum membenarkan dan menyebarkan informasi. Hal inisesuai dengan firman Allah yang bermakna “Wahai orang-orang yang beriman, apabila datangkepada kalian orang fasiq dengan membawa berita, maka periksalah dahulu dengan teliti, agarkalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, lalu kalian menyesal akibat perbuatanyang telah kalian lakukan.”( Q.S Al-Hujurat : 6)
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta di kriteria kebenaran. Pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada jenis pengetahuan (the kind of knowledge) dan teori tentang kebenaran (the theory of truth) pengetahuan.
Fokus lain pada pembahasan epistemologi di atas adalah tentang teori-teori kebenaran pengetahuan, dapat digambarkan teori-teori itu adalah korespondensi, koherensi, pragmatis, performatif, konsensus, dan agama. Konstruksi pemikiran epistemologi khususnya teori-teori kebenaran yang terdapat dalam makalah ini tentu tidak dapat mengeksplor kerangkapemikiran epistemologi secara keseluruhan. hal ini dikarenakan, teori-teori yang tersaji belum mencakup semua teori kebenaran yang ada.
Terakhir adalah keenam teori kebenaran tersebut dapat digunakan masyarakat luas sebagai cara dalam penerimaan berita. Agar masyarakat dapat berperilaku bijak tidak termakan berita yang belum jelas kevalidannya.
Di sisi lain, terkait fenomena hoax dan infodemi yang mewabah dalam jagat media sosial (medsos) di Indonesia melalui sudut pandang Filsafat Analitik John L. Austin dapat dijelaskan sebagai berikut. Hoax dan infodemi hadir melalui luberan informasi di media sosial yang lazim di era post-truth. Kebenaran objektif tidak menjadi acuan untuk menimbang dan mengelola validitas informasi. Rasionalitas diacuhkan, diganti dengan emosi untuk meneguhkan keyakinan.
Hasil yang dicapai pada penelitian ini ada tiga. Pertama, post-truth ialah kondisi di mana kondisi objektif tidak lagi dijadikan sumber untuk menguji validitas informasi, ia telah digantikan oleh keyakinan personal. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi memfasilitasi penggunanya untuk membuat konten hoax untuk disebarluaskan secara massif.
Kedua, pemikiran Austin mengarah pada tiga jenis tindak-bahasa yakni, tindak lokusi, tindak ilokusi, tindak perlokusi. Ketiga, konten hoax ialah jenis ucapan performatif yang bersemayam dibalik ucapan konstantif. Hoax telah melanggar syarat ucapan performatif yakni ketidaktulusan sehingga ia menjadi tidak layak.
Dengan kesimpulan tersebut, untuk menyikap labirin hoax dan infodemi perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman literasi mendalam terkait cara menyaring kebenaran dari melubernya infomasi saat terjadi pandemi Covid-19 ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak yang belum diungkap dalam tulisan ini dan perlu eksplorasi terhadap persoalan yang lebih mendalam lagi. Kritik dan saran penulis terima secara terbuka.(*)
Daftar Pustaka
Bakhtiar, Amsal. Filsafat Ilmu (Jakarta: Rajawali Press,1994)
Fautanu, Idzam. Filsafat Ilmu; Teori dan Aplikasi (Jakarta: Referensi, 2012).
Gallagher, Kenneth T. The Philosophy of Knowledge (Epistemologi, Filsafat Pengetahuan), terj.
P. Hardono Hadi, (Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1994)
Hadi, Hardono. Epistemologi: Filsafat Pengetahuan (saduran dari “The Philosophy of
Knowledge”, by Kenneth T. Gallagher,(Yogyakarta, Kanisius.1994)
Kuhn, Thomas. The Structure of Scientifc Revolution (Chicago: University of Chicago Press,
1962).
Lubis, Akhya. Pemikiran Kritis Kontemporer dari Teori Kritis, Cultural Studies, Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
Muhadjir, Noeng. Filsafat Ilmu; Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme,
(Yogyakarta: Rakesarasin, 2001, Edisi-2).
Manser, M. H. (1996). Oxford Learner’s Pocket Dictionary. Oxford: Oxford uiversity Press.
Nasrullah, Rully, Teori dan Riset Media Siber (cyberspace), (Jakarta,
Prenadamedia Grup. 2014)
Nasrullah, Rully. Media Sosial, (Jakarta, Simbiosa Rekatamedia. 2015)
Reynolds, Martin (2011). Critical thinking and systems thinking: towards a critical literacy for
systems thinking in practice. In: Horvath, Christopher P. and Forte, James M. eds.
Critical Thinking. New York, USA: Nova Science Publishers
Suriasumantri, Jujun S., Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2000)
Susanto, A. Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan
Aksiologis, (Jakarta:Bumi Aksara, 2011)
Suseno, Magnis Franz. 12 Tokoh Etika Abad ke-20, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
*Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya






