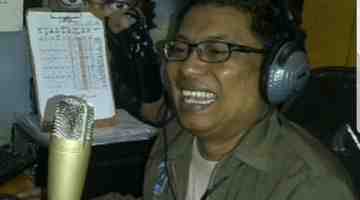Kearifan lokal kelompok etnis adalah kumpulan nilai, praktik, pengetahuan, dan tradisi yang diwariskan dalam suatu komunitas etnis sebagai hasil interaksi panjang mereka dengan lingkungan alam dan sosial. Kearifan lokal ini terbentuk dari pengalaman turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas serta jati diri kelompok etnis. Nilai-nilai ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti adat istiadat, cara hidup, kepercayaan, bahasa, serta sistem sosial yang berperan penting dalam menjaga kohesi sosial dan harmonisasi dengan alam.
Lebih dalam lagi bahasa daerah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang mencerminkan identitas, nilai, dan sejarah suatu komunitas etnis.
Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, bahasa daerah memainkan peran penting dalam menjaga keberagaman budaya, memperkaya literatur, dan memperkuat hubungan antargenerasi. Namun, di tengah pesatnya urbanisasi dan modernisasi, penggunaan bahasa daerah di perkotaan mulai berkurang. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan besar dalam mempertahankan kearifan lokal di kota-kota besar yang sarat dengan tekanan globalisasi dan dominasi bahasa nasional maupun bahasa asing.
Di lingkungan perkotaan, bahasa nasional seperti bahasa Indonesia mendominasi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan media. Bahasa daerah, yang dulunya menjadi bahasa sehari-hari di komunitas lokal, kini mulai jarang digunakan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan bahasa nasional dan asing. Banyak keluarga di kota besar cenderung tidak lagi mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak mereka, dengan alasan agar lebih mudah beradaptasi di lingkungan yang multikultural dan kompetitif. Akibatnya, generasi muda semakin terasing dari bahasa daerah mereka sendiri, yang secara perlahan memutuskan warisan budaya yang seharusnya diteruskan antar generasi.
Berbagai studi menunjukkan bahwa berkurangnya penggunaan bahasa daerah dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Bahasa daerah memuat pengetahuan lokal, filosofi hidup, serta pandangan dunia yang diwariskan turun-temurun, yang berpotensi punah jika tidak lagi digunakan dan diajarkan. Selain itu, kehilangan bahasa daerah juga berdampak pada keterikatan sosial dan kohesi di antara anggota komunitas, mengingat bahasa merupakan sarana penting dalam memperkuat solidaritas dan rasa memiliki terhadap budaya asal.
Permasalahan ini juga melanda masyarakat Kota Surabaya yang menjadi salah satu kota besar di Indonesia, kota yang punya keragaman masyarakat akan budaya dan sejarah. Arus global dan perkembangan kota menjadikan Kota Surabaya sebagai destinasi kepentingan masyarakat yang kompleks. Tantangan akan identitas sosial budaya berupa kearifan lokal menjadi semakin besar, dan dalam konteks ini bagaimana menjaga identitas kearifan lokal berupa mempertahankan penggunaan bahasa daerah masyarakat kota Surabaya.
Bahasa masyarakat Surabaya didominasi dengan bahasa jawa dialek Surabaya yang khas atau yang sering disebut Boso Suroboyoan. Dialek ini memiliki ciri khas tersendiri (unik) yang berbeda dengan bahasa jawa daerah lain seperti Yogyakarta ataupun Solo atau sebagian daerah di timur propinsi Jawa Timur. Boso Suroboyoan terkenal dengan karakteristiknya yang ceplas ceplos, penuh ekspresi, lugas, tidak terlalu menampakkan strata bahasa seperti bahasa Jawa umumnya, dan itu mencerminkan identitas masyarakat kota Surabaya yang terkenal berani, terus terang dan tegas.
Berikut adalah beberapa ciri khas yang kita bisa simak di masyarakat
1. Dialek khas dan penggunaan kosakata unik; Boso Suroboyoan memiliki kosakata yang unik seperti sebutan cak (untuk laki laki) dan ning (untuk perempuan), sapaan rek untuk teman, yo opo yang berarti bagaimana, koen untuk penyebutan kamu dan lain sebagainya. Secara dialek juga jika disimak berbeda dengan masyarakat jawa lainnya, dan itu kekhasannya sangat identik sekali masyarakat kota Surabaya
2. Intonasi yang tegas dan nada lantang; Boso Suroboyan cenderung bersifat egaliter dalam komunikasi yang ini terasa berbeda dengan bahasa jawa Mataraman (sebutan untuk bahasa Jawa masyarakat kerajaan Mataram). Strata bahasa sering tidak terlihat dalam hal intonasinya. Gaya berbicara ini sering dianggap keras atau bahkan kasar oleh orang luar, tetapi sebenarnya merupakan bentuk keakraban dan cara berbicara yang spontan serta ekspresif.
3. Pelafalan yang lebih terbuka; Boso Suroboyoan memiliki pelafalan yang lebih terbuka dan penekanan pelafalan di ujung kata sangat tegas.
4. Penggunaan kata-kata seruan; Boso Suroboyoan dikena dengan seruan yang kuat sebagai bagian dari ekspresi emosi bukan sekedar sebagai makian. Kata kata seruan ini menunjukkan keakraban walaupun terdengar kasar seperti kata ”jancok” atau ”nggateli kok”. Dalam konteks Boso Suroboyan itu lebih menunjukkan sikap asertif dan solidaritas
Sayangnya di tengah modernisasi dan globalisasi penggunaan Boso Suroboyoan mulai berkurang di kalangan generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia terutama di lingkungan formal dan media sosial. Fenomena ini tentu menjadi tantangan dalam melestarikan dialek Boso Suroboyan sebagai bagian dari identitas Kota Surabaya.
....
Sebenarnya, permasalahan tergerusnya penggunaan bahasa sebenarnya tidak hanya dialami oleh masyarakat Kota Surabaya saja, melainkan sudah menjadi problematika di belahan bumi lainnya. Beberapa contoh bahasa yang tercatat pernah ada tapi sekarang sudah punah atau hilang seperti bahasa ”Akkadia” yaitu bahasa yang pernah digunakan Etnis Mesopotamia kuno sekitar 2500SM yang juga menjadi bahasa utama dalam pemerintahan Babilonia dan Asyur.
Ada pula bahasa ”Koptik Mesir” yaitu bahasa Mesir kuno yang digunakan komunitas kristen Mesir (Koptik) yang punah sekitar abad 17 karena digantikan bahasa Arab sebagai bahasa utama di Mesir, dan banyak lagi contoh bahasa yang punah dan hilang karena sudah tidak lagi digunakan dalam bahasa keseharian.
Dari perspektif di atas, pengikisan penggunaan Boso Suroboyoan oleh masyarakat Kota Surabaya dapat dipahami sebagai akibat dari interaksi banyak faktor yaitu penggunaan bahasa dominan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di wilayah formal, berkurangnya pewarisan Boso Suroboyoan di lingkungan keluarga, berkurangnya dukungan institusional, serta bagaimana besarnya pengaruh modernisasi dan globalisasi
Tanpa intervensi semua pihak untuk mempertahankan dan mempromosikan Boso Suroboyoan di pelbagai ruang baik formal maupun informal, Boso Suroboyoan ini beresiko semakin terpinggirkan dan akan terancam kepunahan. Untuk pelestarian Boso Suroboyoan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat kota Surabaya, kiranya diperlukan langkah-langkah strategis yang mempertimbangkan konsep dan faktor yang telah dibahas pada tulisan ini
Berikut adalah beberapa langkah rekomendasi untuk pelestarian Boso Suroboyoan yang bisa dilakukan:
1. Dukungan Institusional dan Kebijakan Pendidikan
2. Pewarisan Boso Suroboyoan antar generasi dalam keluarga
3. Peningkatan penggunaan Boso Suroboyoan di media sosial
4. Penggunaan Boso Suroboyoan dalam ruang publik dan komunitas
5. Dokumentasi Bahasa berupa kamus Boso Suroboyoan
6. Penggunaan Boso Suroboyoan di ruang formal dan informal
7. Kolaborasi dengan Institusi Riset dan Kampus
Melestarikan Boso Suroboyoan memiliki nilai yang signifikan dalam menjaga warisan budaya, meningkatkan solidaritas sosial, menguatkan ikatan antar generasi, serta mendukung keragaman bahasa dan budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kebanggaan menggunakan Boso Suroboyoan dalam keseharian akan memperkuat identitas diri, identitas karakter masyarakat Kota Surabaya yang tegas, berani, egaliter, dan apa adanya.
Depi Priyono, M.Pd
Mahasiswa S3 Pendidikan IPS Unesa