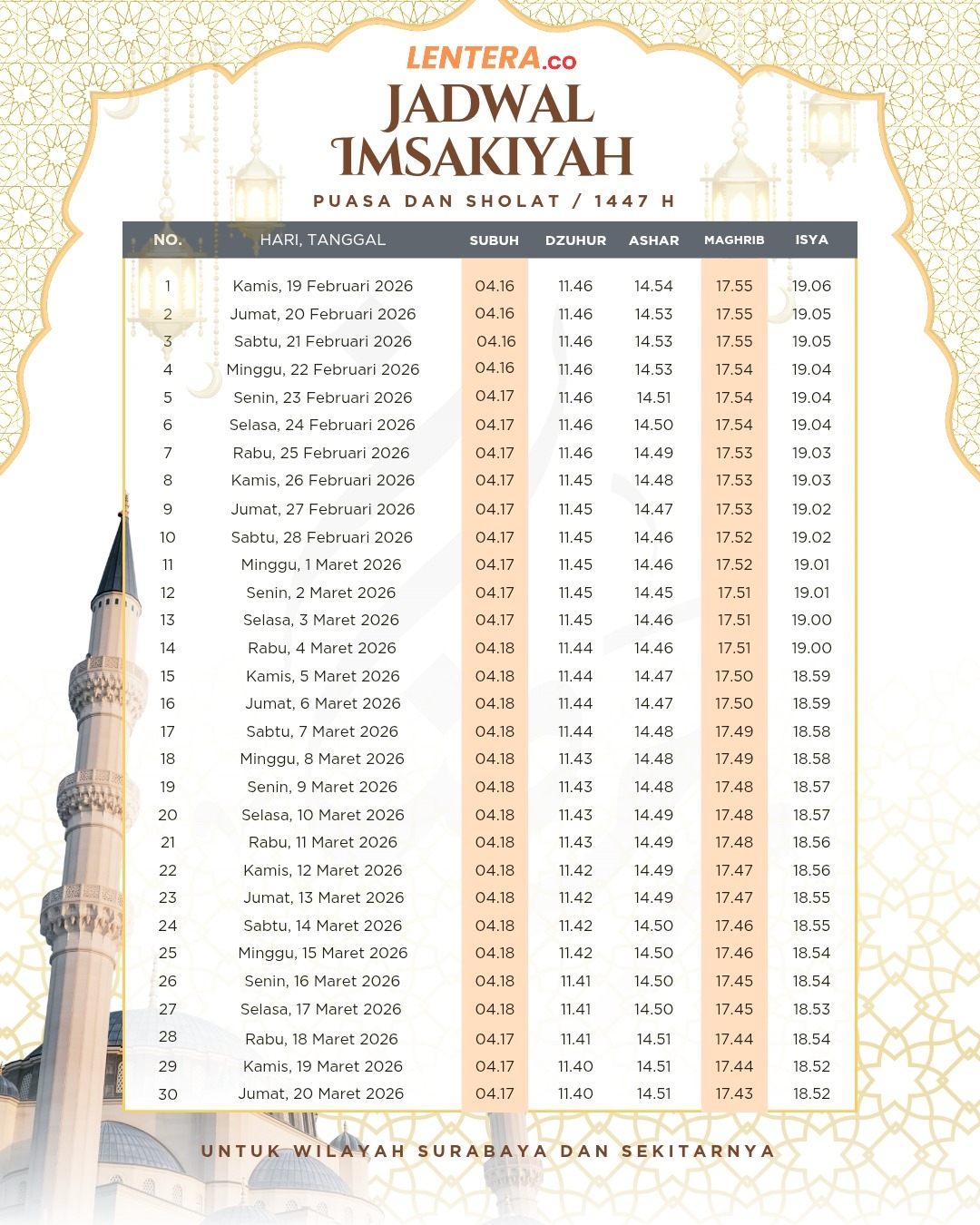MALANG (Lenteratoday) -Melalui film dokumenter bertajuk HULA-KETA: Bukan Maluku Tanpa Sagu, seolah menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia, bahwa identitas makanan dari suatu daerah merupakan bagian dari sebuah kebudayaan yang ada di Indonesia.
Hal tersebutlah yang sengaja ingin disampaikan oleh produser film HULA-KETA, Daya Negeri Wijaya, saat mengadakan pemutaran perdana film tersebut, di salah satu bioskop di Kota Malang. Dijelaskannya bahwa Hula berartikan sagu sedangkan Keta bermakna panggang yang merujuk pada cetakan dari sagu.
“Kenapa kemudian kita membuat judul bukan Maluku tanpa sagu, karena kita melihat sagu menjadi identitas dari orang Maluku, terutama Maluku Utara dalam hal ini adalah Tidore. Jadi mereka bukan hanya tidak bisa lepas dari makanan sagu tapi juga hidup dari sagu itu sendiri,” ujar Daya, ditemui usai acara tersebut, Sabtu (18/3/2023).
Daya menambahkan, bagian tak kalah penting dengan adanya film dokumenter tersebut adalah dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mengetahui dan melestarikan kebudayaan, melalui hal-hal yang dianggap kecil, yang sering ditemui dalam keseharian, seperti sagu tersebut.
“Jadi dengan adanya film ini bukan hanya orang Maluku yang dapat melestarikan budaya. Tapi kita orang Jawa, luar Maluku Utara pun bisa mengetahui kebudayaan Indonesia. Sehingga memunculkan apa yang disebut dengan kesadaran budaya. Artinya kita bisa melestarikan budaya Indonesia yang sangat beraneka ragam ini,” tambahnya.
Pria yang berprofesi sebagai Dosen Ilmu Sejarah di Universitas Negeri Malang (UM), ini kemudian menjelaskan lebih dalam terkait dengan makna HULA-KETA: Bukan Maluku Tanpa Sagu. Disebutkannya, sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada abad 17 silam. Tidak ada penyebutan khusus mengenai olahan sagu di Maluku Utara.
Hal yang sama juga terjadi pada alat pencetak sagu, yakni Keta. Dijelaskannya, selama ini di pasaran pun masyarakat lebih mengenal nama Forno yang merujuk kepada Keta. Dimana Forno, adalah bahasa bangsa Eropa untuk mengartikan panggangan dari adonan roti sagu. 2 hal itulah yang menambah nilai tersendiri sebab adanya persilangan budaya dalam konteks bahasa asing pada film tersebut, sambung Daya.
“Karena yang memperkenalkan roti sagu adalah orang-orang Eropa yang pada waktu itu kehabisan bahan makanan. Singkat ceritanya seperti itu. Kemudian untuk bahan cetakan roti yang digunakan untuk memanggang. Orang Eropa ini menyebut dengan sebutan Forno, kalau orang Maluku menamakan Keta. Tapi sampai sekarang, di pasaran pun lebih terkenal dengan kata Forno,” paparnya.
Masih menurut Daya, film yang mulai diproduksi pada Januari 2023 ini, dikatakannnya cukup memakan waktu yang tidak sedikit pada masa pra-produksi yakni di bulan November 2022. Selain itu, alasan pemilihan Maluku dan Sagu, juga disebutkan oleh produser film yang difasilitasi oleh Dana Indonesiana dari Kemendikbud RI bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ini.
“Alasannya adalag masalah expertice, saya kan fokus pada ekspansi Portugis di abad 17 sehingga saya bukan hanya melihat perdagangan Portugis atau Spanyol, tapi juga melihat persilangan budaya atau kontak budaya orang luar dan lokal. Dan salah satu yang terlihat adalah Hula Keta ini,” tukas Daya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, di dalam film dokumenter tersebut ada beberapa pesan yang dapat dipetik. Pertama, menurutnya penting untuk mengetahui bahwa di Indonesia ternyata menyimpan banyak kekayaan dan sumber pangan.
Kedua, budaya memakan makanan khas dari orang-orang Maluku, menurutnya juga dapat diadopsi oleh warga Malang dengan memakan olahan tradisional seperti ketela pohon, dan sebagainya.
“Dari pembuatan film ini, semua bisa melihat bahwa sebetulnya kita ini kaya raya dengan sumber pangan yang beraneka ragam. Tinggal kita biasakan, kita budayakan. Boleh makan nasi, dan lain lain. Mungkin disini bisa kita makan ketela pohon yang sudah diolah, disiapkan menjadi makanan pendamping, dimulai dari hal-hal kecil itu,” tegas Pria yang akrab dengan sapaan Bung Edi ini.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH



-jpg.jpg)