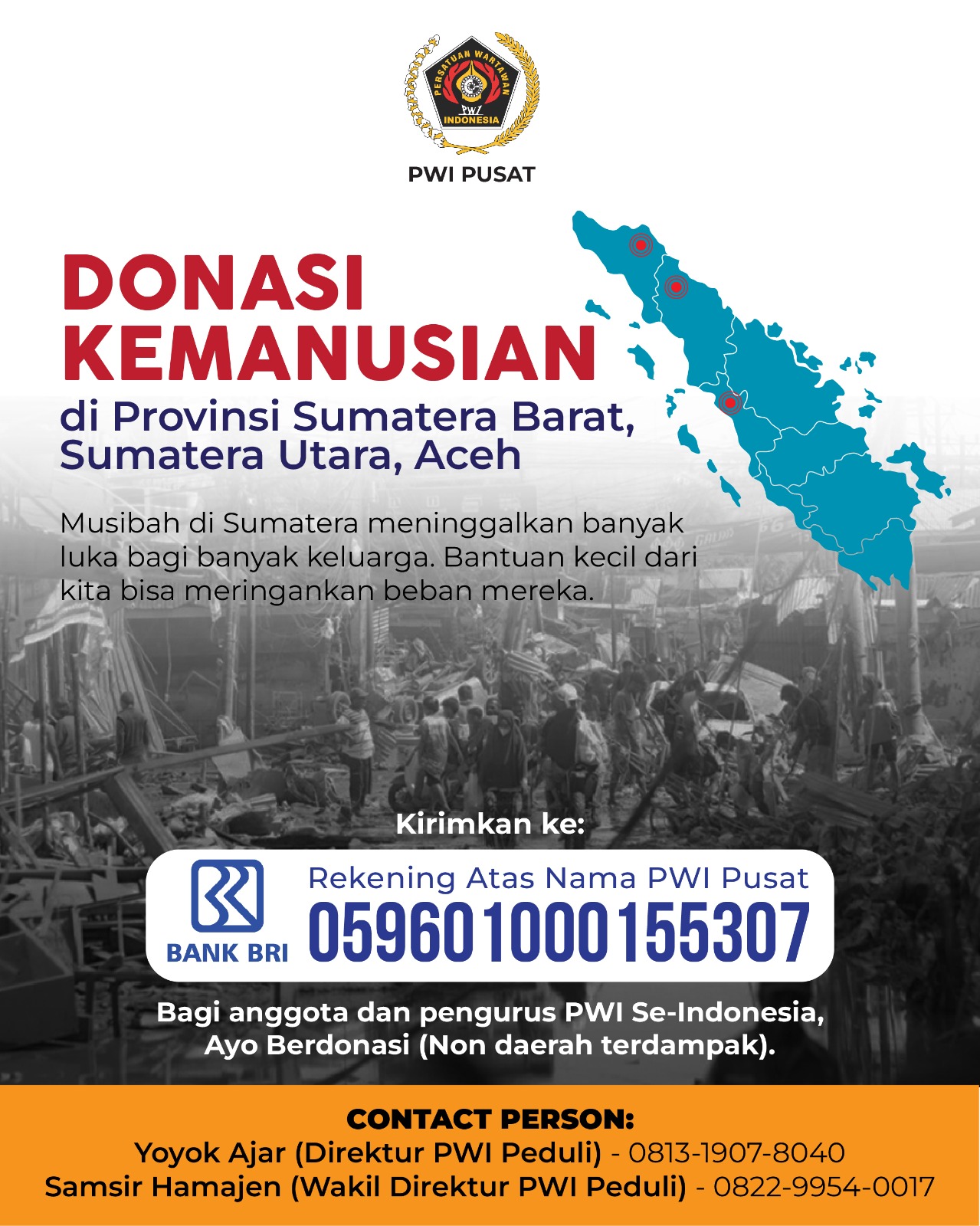Pop Culture sebagai Cara Berkomunikasi: Ekspresi Politik dan Sosial di Balik Kibaran Bendera One Piece
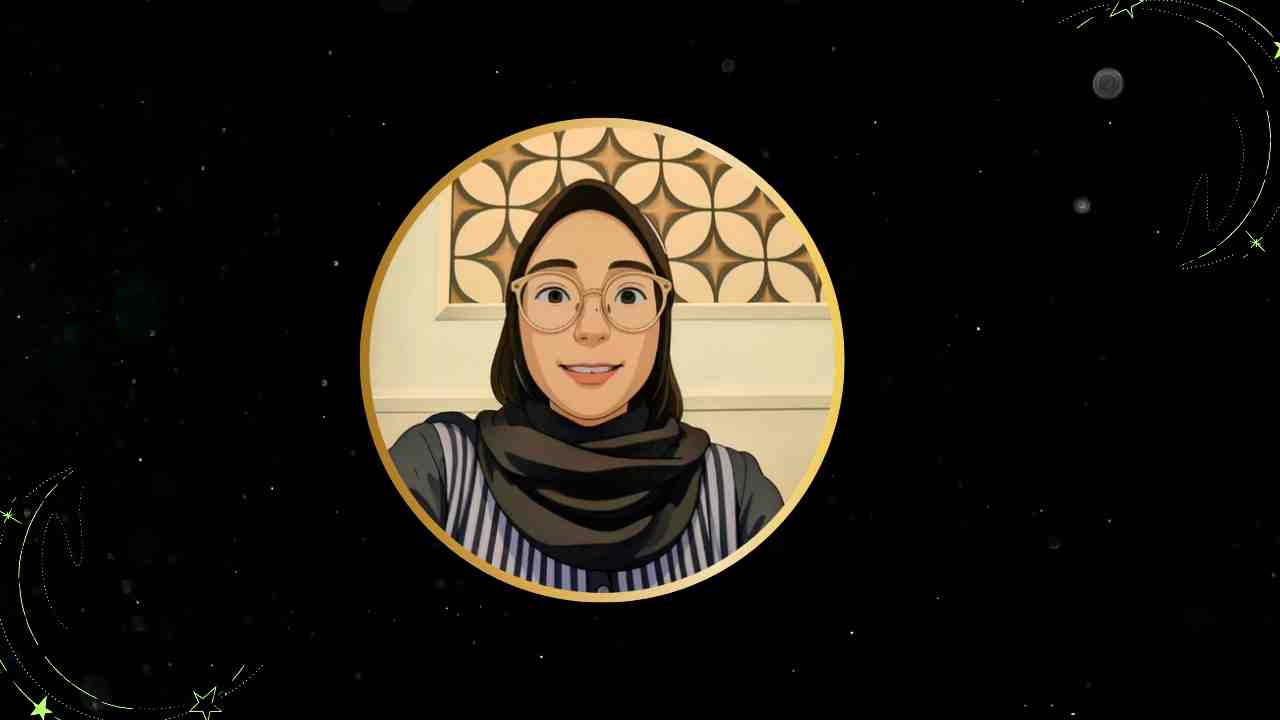
Oleh: A.Widyawati*
DI era digital dan informasi yang serba cepat, budaya populer atau popular culture tidak lagi sekadar menjadi konsumsi hiburan, tetapi berkembang menjadi medium penting dalam menyampaikan pesan sosial dan politik.
Istilah pop culture merujuk pada produk budaya yang digemari dan diproduksi massal, mencakup film, musik, serial televisi, komik, hingga anime dan meme. Dalam konteks komunikasi kontemporer, fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan karya fiksi sebagai alat ekspresi, kritik, dan negosiasi makna sosial-politik.
Salah satu peristiwa aktual yang menarik perhatian adalah pemasangan bendera bajak laut “Straw Hat Pirates” dari anime One Piece menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia 2025.
Aksi ini viral dan menimbulkan reaksi beragam dari publik hingga aparat keamanan. Memperlihatkan bahwa simbol fiksi kini mampu menembus batas antara hiburan dan politik.
Dalam kajian komunikasi budaya, karya fiksi dipahami sebagai konstruksi simbolik yang merefleksikan dan membentuk realitas sosial. Menurut Stuart Hall (1980), makna dalam komunikasi tidak bersifat tetap, tetapi dinegosiasikan secara aktif oleh audiens melalui proses encoding dan decoding. Dengan kata lain, ketika masyarakat memilih untuk mengasosiasikan karakter fiksi seperti Monkey D. Luffy sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, maka terjadi proses resemantisasi budaya fiksi menjadi makna sosial yang aktual.
Proses representasi adalah cara atau proses bagaimana suatu konsep, ide, atau informasi direpresentasikan atau diwakili dalam berbagai bentuk seperti kata-kata, gambar, simbol, atau tindakan.
Di negara lain hal serupa dilakukan. Dalam protes demokrasi di Thailand (2014–2020), demonstran menggunakan tiga jari dari film The Hunger Games sebagai simbol perlawanan.
Sementata, aksi demonstran di Hong Kong (2019) yang mengenakan topeng karakter superhero atau anime sebagai simbol identitas kolektif.
Pop Culture sebagai Komunikasi Politik
Menurut Denis McQuail (2010), komunikasi politik adalah segala bentuk komunikasi yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan publik. Saat karya fiksi digunakan untuk menyampaikan opini politik, maka ia memasuki wilayah “komunikasi politik alternatif” yang bersifat tidak formal namun masif dan berpengaruh.
Dalam teori Framing (Entman, 1993), simbol-simbol populer berfungsi membingkai realitas sosial dan menyederhanakan isu kompleks menjadi narasi yang emosional dan komunikatif.
Hal ini juga sejalan dengan Teori Simbolik Interaksionisme(Blumer, 1969), yang menekankan bahwa makna simbol-simbol sosial ditentukan oleh interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu.
Generasi muda, khususnya Gen Z dan Alpha, hidup dalam budaya digital yang terbuka, interaktif, dan ekspresif. Dalam konteks ini, karya fiksi menjadi bahasa komunikasi antar generasi yang lebih efektif daripada wacana politik konvensional. Pop culture mampu mengkomunikasikan nilai-nilai seperti Keadilan sosial (justice) hingga Anti-otoritarianisme.
Hal ini sejalan dengan konsep Participatory Culture dari Henry Jenkins (2006), yang menyatakan bahwa publik kini tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga produsen aktif dalam menciptakan, memodifikasi, dan menyebarluaskan simbol budaya. Meme, cosplay, hingga pemasangan bendera fiksi adalah bentuk grassroots communication yang seringkali lebih jujur dan langsung daripada komunikasi elite politik.
Bendera One Piece dan Resonansi Simbolik
Fenomena pemasangan bendera bajak laut Straw Hat Pirates dari anime One Piece di sejumlah wilayah Indonesia (Juli–Agustus 2025) menjelang Hari Kemerdekaan menjadi sorotan nasional. Respon aparat yang mengaitkan simbol tersebut dengan potensi makar menuai kritik publik.
Simbol bajak laut tersebut dipersepsi publik sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan; identitas kolektif generasi muda yang merasa tidak diwakili oleh sistem politik mapan dan bentuk sindiran dan satire terhadap figur elite yang dianggap anti-rakyat
Fenomena ini mengindikasikan adanya kegagalan komunikasi negara dengan generasi muda, yang tidak lagi melihat politik dalam bingkai formal, melainkan dalam narasi fiksi yang penuh harapan dan emosi.
Perlu diakui bahwa fenomena ini juga menyimpan ambiguitas. Tidak semua ekspresi berbasis pop culture membawa pesan positif.
Dalam konteks komunikasi publik, penting adanya literasi simbol dan budaya populer oleh pemerintah dan institusi.
Juga harus ada lendekatan persuasif dan dialogis, bukan represif terhadap simbol-simbol budaya yang berkembang.
Pelibatan ahli komunikasi dan budaya juga penting dalam merumuskan kebijakan yang peka terhadap ekspresi publik.
Karya fiksi dan simbol budaya populer tidak lagi bisa dianggap remeh atau apolitis. Dalam konteks komunikasi kontemporer, ia telah menjadi alat komunikasi sosial dan politik yang efektif, khususnya bagi generasi digital. Ilmu komunikasi ditantang untuk membaca dinamika ini sebagai ekspresi naratif publik yang sah dan bermakna, bukan sekadar fenomena viral.
Di tengah maraknya penggunaan simbol budaya populer, penting untuk tetap menempatkan Bendera Merah Putih sebagai simbol pemersatu bangsa dan identitas nasional yang tidak tergantikan. Bendera Merah Putih bukan sekadar kain berwarna, melainkan lambang perjuangan, pengorbanan, dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ekspresi budaya dan komunikasi politik harus tetap menjunjung tinggi dan menghormati simbol-simbol negara sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap sejarah dan integritas bangsa.
*Penulis adalah praktisi media sekaligus Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sunan Gresik