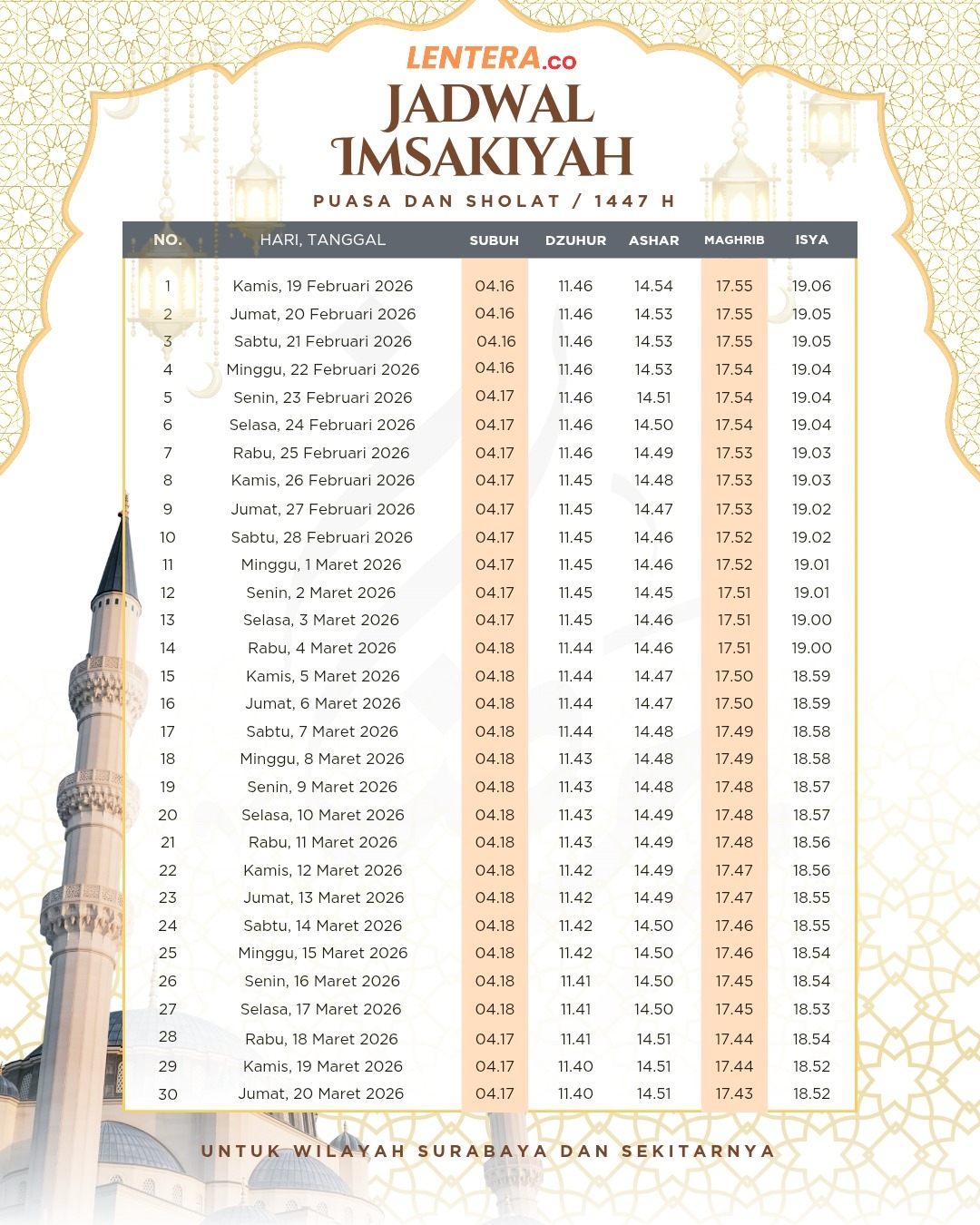SURABAYA (Lentera) - Fenomena "performative male" atau pria performatif sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan telah berkembang menjadi tren global, termasuk di Indonesia. Istilah ini merujuk pada gaya atau citra diri yang dibangun oleh sebagian pria, terutama dari Generasi Z, sebagai respons terhadap dinamika sosial yang kian berkembang. Mereka menciptakan persona yang dianggap "progresif" dan "sensitif" untuk mendapatkan daya tarik di mata perempuan dan lingkungan sosial.
Buktinya, tren ini tidak hanya terbatas di dunia maya. Sebuah kontes "performative male" bahkan pernah diadakan di Jakarta, yang dokumentasinya diunggah oleh akun media sosial @ussfeeds. Ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut telah bergeser dari sekadar wacana digital menjadi bagian dari budaya pop di kehidupan nyata.
Kontes tersebut seolah menjadi panggung bagi para pria untuk menampilkan atribut-atribut yang mencerminkan citra ideal ini, seperti membawa buku feminis, gitar akustik, atau kamera analog—semua demi citra diri yang unik dan menarik secara visual.
Apa itu Pria Performatif?
Menurut media massa Stuff, pria performatif adalah sosok yang menampilkan citra progresif, terlihat lembut, dan sadar secara emosional, namun semua itu hanya di permukaan. Mereka mungkin fasih berbicara tentang isu kesehatan mental, membaca buku-buku feminis, atau mendengarkan musisi indie yang sedang naik daun.
Namun, inti permasalahannya adalah motivasi di balik semua tindakan ini. Perilaku tersebut sering kali tidak didasari oleh pertumbuhan pribadi yang autentik, melainkan didorong oleh keinginan untuk terlihat menarik dan diterima oleh perempuan modern. Berikut adalah ciri-ciri pria performatif:
Persona Tampilan
Mereka membangun citra yang secara stereotip dianggap berlawanan dengan maskulinitas tradisional. Atribut yang sering digunakan mencakup tote bag, minum matcha, rajin menjalani terapi, hingga memahami astrologi atau zodiak. Tampilan ini seolah-olah menunjukkan bahwa mereka adalah pria yang peka, artistik, dan berpikiran terbuka.
Konten di Media Sosial
Citra ini dikemas secara apik dan estetik di platform seperti TikTok dan Instagram. Konten mereka sering kali berfokus pada "healing", "self-love", dan "self-care" dengan narasi yang sarat akan kesadaran emosional.
Motivasi di Balik Tindakan
Hal yang membedakan mereka dari pria yang benar-benar peduli adalah motivasinya. Citra ini dibangun bukan karena ketertarikan pribadi yang tulus, melainkan demi validasi dan daya tarik dari lingkungan sosial. Mereka tahu betul citra ini disukai, dan mereka memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi.
Menurut Psikologis
Fenomena ini sejatinya memiliki sisi positif karena secara tidak langsung menantang pola pikir maskulinitas yang kaku dan kolot. Namun, masalah muncul ketika fokus mereka hanya pada tampilan luar. Mereka lebih mementingkan estetika dan kesan yang ditimbulkan, alih-alih meresapi dan benar-benar memahami pemikiran yang mendalam di balik isu-isu yang mereka suarakan.
Di balik kesan lembut dan terbuka, ada dorongan kuat akan validasi, status, dan kontrol. Mereka menggunakan persona ini sebagai alat untuk memanipulasi persepsi orang lain. Pria performatif mungkin mahir menarik perhatian karena citra mereka yang lembut dan berpikiran terbuka, tetapi mereka kesulitan membangun koneksi emosional yang nyata. Mereka bisa saja berbicara tentang luka batin dan trauma, tetapi menghindar saat diminta untuk bertanggung jawab atau terlibat dalam percakapan yang lebih serius. Ketika dikritik, mereka cenderung menempatkan diri sebagai korban, bukan pelaku.
Kajian Gender dan Evolusi Sejarah
Fenomena "performative male" bukan sekadar tren tanpa dasar; ia dapat dianalisis melalui lensa kajian gender. Teori "doing gender" oleh Candace West dan Don Zimmerman (1987), serta gagasan performativitas gender dari Judith Butler, menjelaskan bahwa gender, termasuk maskulinitas, bukanlah bawaan biologis, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dibentuk melalui tindakan berulang yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
Penelitian Hsing-Yuan Liu (2022) mengkaji maskulinitas performatif yang cenderung menampilkan citra tangguh untuk mempertahankan citra maskulin. Namun, tren "performative male" saat ini menampilkan evolusi dari konsep tersebut. Alih-alih citra tangguh, mereka membangun citra "sadar sosial" atau "terbangun" yang kini dianggap menarik oleh perempuan dan komunitas progresif. Perilaku ini, ironisnya, sering kali hanya berfungsi sebagai strategi branding belaka.
Konsep ini juga bukan hal yang sepenuhnya baru. Sejarah menunjukkan adanya pola serupa yang muncul di berbagai era:
Era 1970-an
Di tengah gelombang feminisme kedua, banyak pria yang mengaku sebagai pendukung gerakan perempuan. Namun, motif di balik dukungan itu sering kali adalah untuk mendekati perempuan atau menghindari kritik sosial. Mereka mungkin tampak pro-feminis tetapi masih melakukan mansplaining atau menghindari tanggung jawab emosional.
Era 1990-an
Budaya pop memperkenalkan sosok "pria bohemian" atau "sad boy" melalui karakter-karakter film seperti Reality Bites dan High Fidelity. Mereka tampil sebagai sosok yang emosional dan mendalam, namun sering kali memiliki sisi manipulatif.
Saat ini, estetika tersebut telah berevolusi mengikuti zaman. Jika di masa lalu atributnya adalah puisi dan musik eksperimental, kini digantikan oleh atribut modern seperti matcha, tote bag, dan diskusi kesetaraan gender di kafe. Perubahan ini menunjukkan bahwa inti dari performativitas gender—yaitu menampilkan diri demi validasi sosial—tetap relevan, hanya saja dengan wajah dan atribut yang berbeda.
Pada akhirnya, fenomena ini menjadi pengingat penting bahwa autentisitas jauh lebih berharga daripada sekadar estetika. Pertumbuhan diri yang sesungguhnya seharusnya dilakukan untuk diri sendiri, bukan untuk mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber